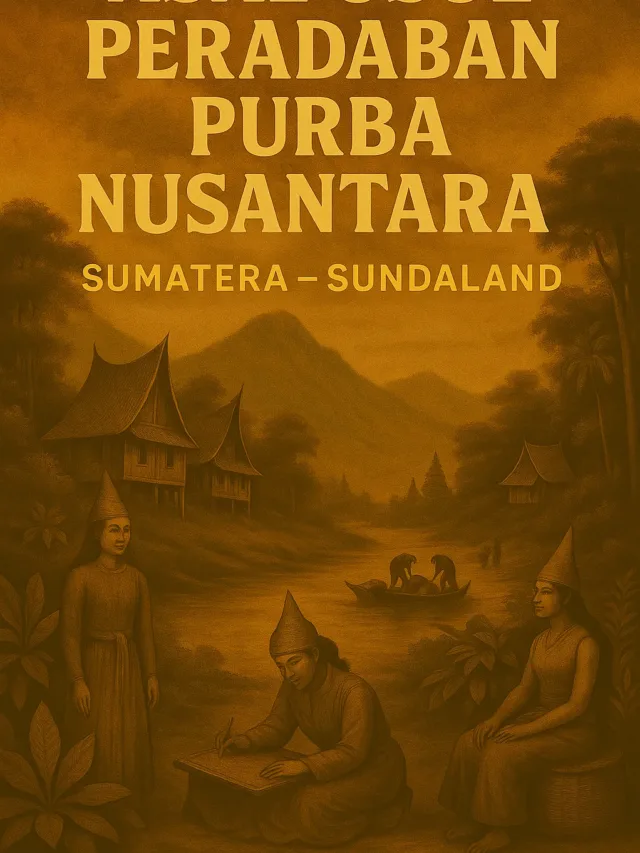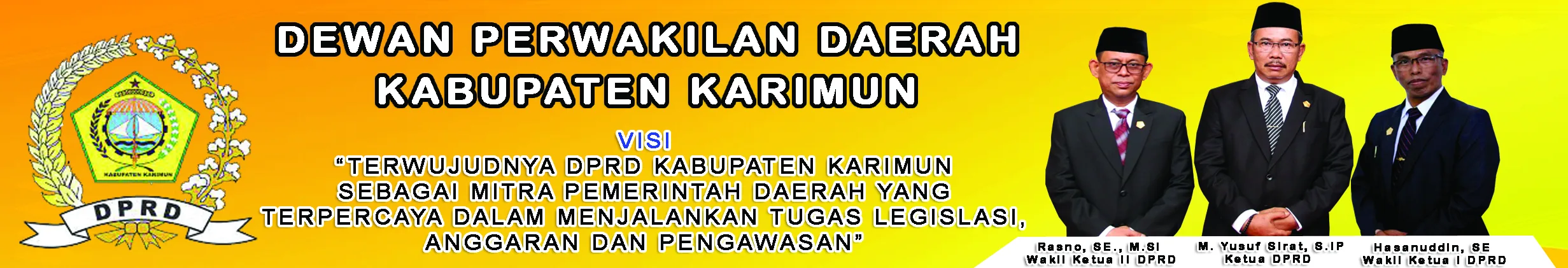KUTIPAN – Sekolah itu berdiri tenang di Desa Bakong. SMPN 2 Singkep Barat namanya. Sekilas tak ada yang salah dari bangunannya. Dinding kokoh, atap terpasang, papan nama pun masih menyala gagah di depan gerbang. Tapi jangan terkecoh dulu. Di balik ketenangan sekolah itu, ada satu hal yang bikin kepala gurunya mendongak tiap kali awan mulai gelap dan mendung bergulung: tanah di tepi sekolah yang rawan longsor.
Kalau di kota, masalah sekolah mungkin seputar WiFi lambat atau AC yang rusak. Tapi di sini, di ujung barat Singkep, masalahnya bukan sekadar kenyamanan belajar, tapi keselamatan nyawa anak-anak. Bukan lebay. Kepala sekolahnya sendiri, Bu Sri Andhayani, sudah menyuarakan kekhawatiran ini sejak lama.
“Kami dari pihak sekolah sangat membutuhkan sekali adanya pembangunan batu miring atau pun tembok penahan tanah,” kata beliau, dengan nada yang bukan hanya formalitas pejabat, tapi nada seorang ibu yang sedang menjaga anak-anaknya.
Hujan bagi sebagian orang adalah romantika. Tapi bagi warga sekolah ini, hujan adalah tanda bahaya. Air yang turun deras bakal bercampur dengan tanah dari bukit dan langsung menyerbu halaman depan sekolah. Becek sih biasa, tapi kalau air sudah bawa serta gerakan tanah, itu bukan main-main.
Bu Sri tahu benar apa yang dipertaruhkan. Ia sudah membayangkan kemungkinan terburuk: “Yang sangat kita khawatirkan, apabila di jam sekolah tiba-tiba ada runtuhan tanah, itu sangat membahayakan anak didik.”
Bayangkan kalau anak-anak sedang upacara, atau main bola, atau sekadar antre beli jajanan di kantin, lalu tiba-tiba tanah di atas sana memutuskan untuk tidak diam di tempatnya. Siapa yang bisa disalahkan? Hujan? Bukit? Alam? Atau kita sendiri yang sudah terlalu biasa menunda hal-hal penting sampai bencana datang mengetuk?
Sekolah ini hanya minta satu hal: tembok. Tapi bukan sembarang tembok. Ini bukan soal estetika atau proyek padat karya. Ini tentang pengaman nyawa. Tentang memastikan anak-anak bisa belajar tanpa dihantui ketakutan bakal diseruduk tanah longsor sewaktu-waktu. Tentang memberi rasa aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman setelah rumah: sekolah.
Panjang tembok yang dibutuhkan kira-kira 50 sampai 100 meter. Panjang yang lebih pendek dari jalan menuju jabatan, tapi lebih panjang dari daftar alasan kenapa pembangunan sering tertunda. Kalau pemerintah masih juga tak gerak, maka tembok itu akan tetap jadi mimpi yang tertahan. Dan tanah? Tanah tak kenal kompromi.
Ini bukan soal marah-marah. Ini juga bukan soal menuntut dengan suara tinggi. Tapi ini soal mendesak mereka yang punya kuasa untuk sedikit saja berpaling dari meja rapat dan menengok ke ujung Singkep Barat. Di sana ada sekolah yang menanti. Di sana ada anak-anak yang ingin belajar tanpa harus melihat bukit di belakang mereka sebagai ancaman.
Jadi, sebelum tanah itu benar-benar bergerak, bisakah kita—atau siapa pun yang punya wewenang—bergerak lebih dulu?
Laporan: Yuanda Editor: Fikri