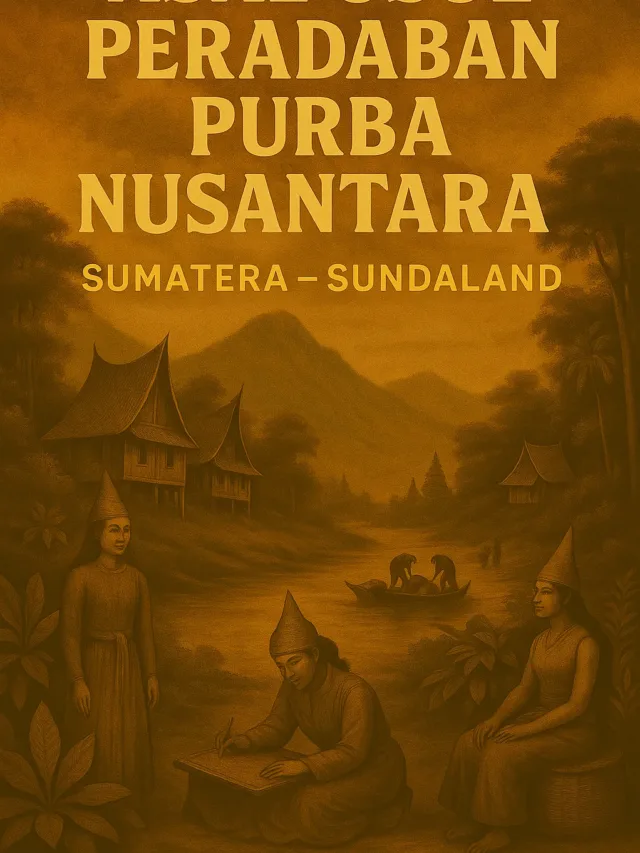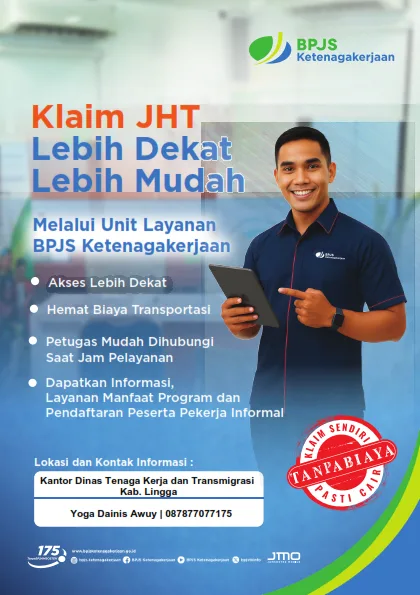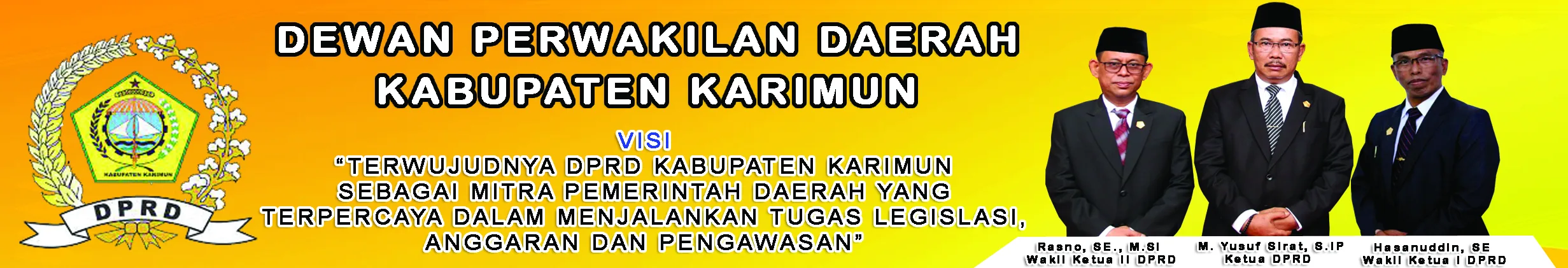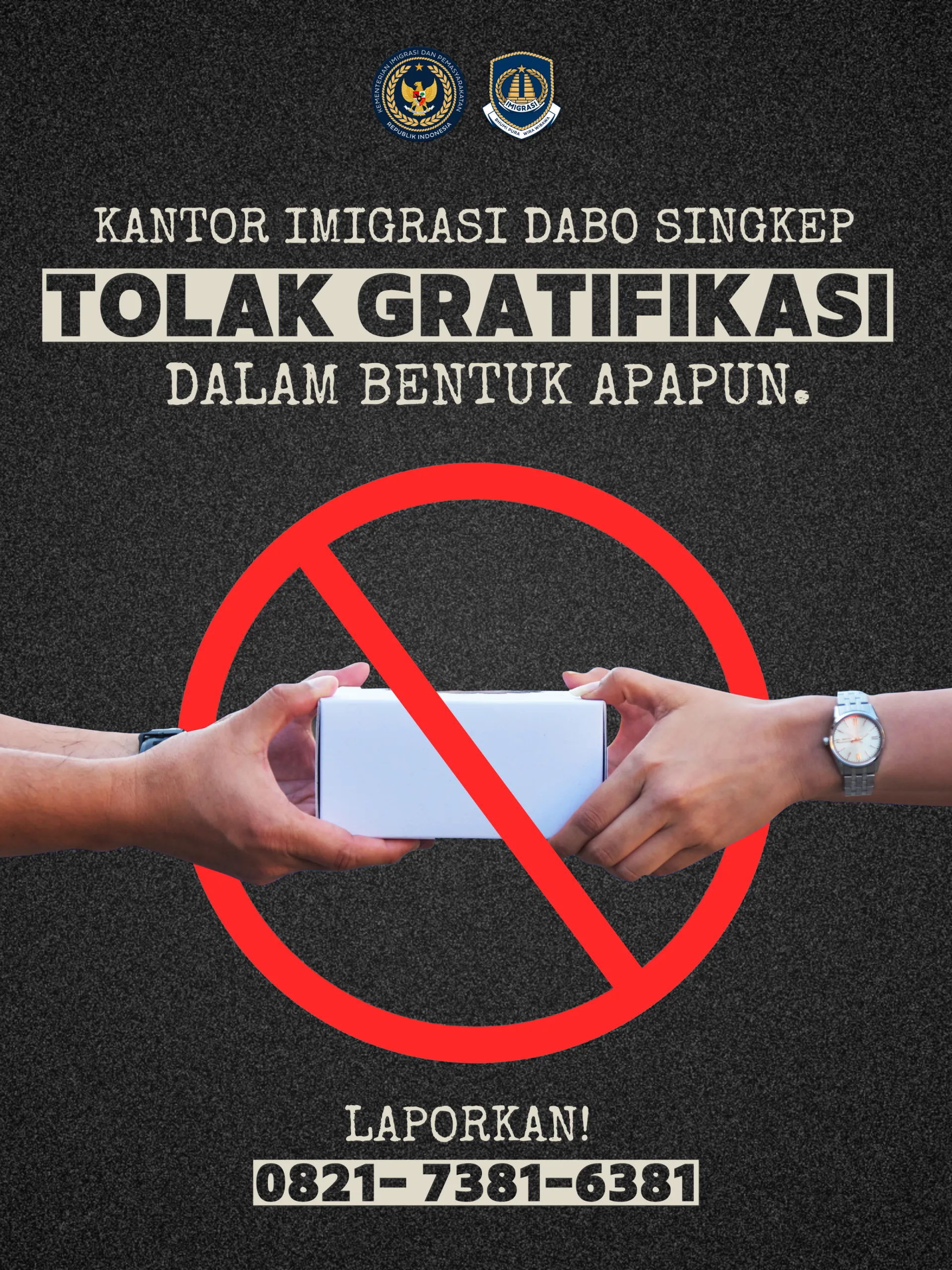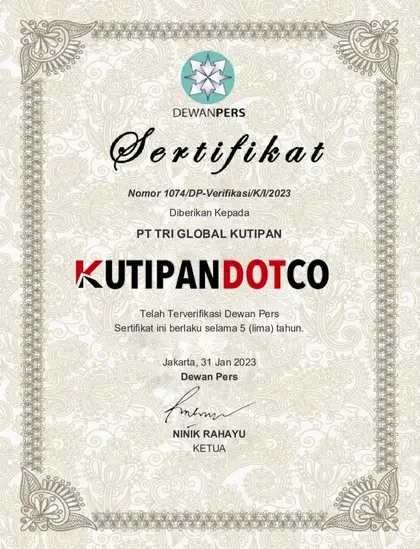Oleh: Encik Ryan Pradana Fekri, ST.,M.PWK.
(Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota, Pengajar di Institut Teknologi Nasional Bandung, Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia)
Batam, Bintan, dan Karimun telah lama menjadi primadona perdagangan Indonesia dengan statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Bahkan pemerintah pada tahun 2024 lalu telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebagai upaya untuk terus mengakselerasi pengembangan di kawasan ini.
Tahun ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai dasar hukum baru untuk penyesuaian dan peningkatan implementasi FTZ. Namun, setelah lebih dari satu setengah dekade sejak tahun 2007 lalu, sebuah pertanyaan kritis mengemuka: sudahkah manfaat FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merembes secara signifikan ke wilayah-wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau?
Dominasi FTZ Batam, Bintan, dan Karimun
Pertumbuhan ekonomi Batam, Bintan, dan Karimun selama 10 tahun terakhir berdasarkan data BPS Provinsi Kepri menunjukkan dominasi, bahkan selama rentang tahun 2023 sampai dengan 2024 pertumbuhan ekonomi ketiganya berada di kisaran 5,5 persen hingga 8,89 persen melesat meninggalkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.
Lebih dari 70 persen Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Provinsi Kepri terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Karimun. Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Kepri realisasi PMA di Kota Batam pada tahun 2024 mencapai US$1.153.558,89, berkontribusi sekitar 46,18 persen dari total investasi PMA di Provinsi Kepri. Data ini mengonfirmasi sebuah realitas bahwa FTZ masih menjadi “menara gading” yang aktivitas ekonominya berputar-putar di dalam batasannya sendiri.
Teori ekonomi mengenai pertumbuhan kutub (growth pole theory) menjelaskan bahwa pertumbuhan bermula dari pusat-pusat tertentu yang kemudian diharapkan menyebar ke wilayah sekitarnya (spread effects). Namun, teori ini juga mengakui bahwa adanya efek negatif, yaitu backwash effects, di mana sumber daya seperti modal dan investasi, infrastruktur serta tenaga kerja terampil justru tersedot ke pusat pertumbuhan. Teori ini terasa kontekstual menggambarkan dominasi perkembangan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun saat ini.
Membedah Akar Masalah
Lantas, dimana letak permasalahnnya? Regulasi menjadi titik awal yang perlu dicermati lebih dalam dan dianalisis. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 dan peraturan turunannya, Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun, fokusnya sangat kuat pada penciptaan iklim usaha yang kondusif di dalam FTZ. Insentif fiskal seperti pembebasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai hanya berlaku untuk transaksi dan industri yang beroperasi di dalam Batam, Bintan, dan Karimun.
Kebijakan ini pada satu sisi memang memberikan keleluasan dalam optimalisasi pengembangan FTZ BBK. Tetapi, pada sisi lain memiliki risiko yang dapat menyebabkan disintegrasi rantai pasok. Perusahan-perusahaan manufaktur di Batam, misalnya lebih mudah dan murah mengimpor bahan baku dari Tiongkok daripada membeli dari petani atau pengusaha di Lingga, Anambas atau Natuna.
Biaya logistik antarpulau yang masih tinggi dan infrastruktur yang belum merata serta memadai di luar FTZ sehingga membuat tidak adanya integrasi ekonomi wilayah. Akibatnya adalah: ekonomi modern dan global di FTZ, dan ekonomi tradisional yang berjalan di tempat pada sebagian besar wilayah Kepri lainnya.
Membangun Pemerataan Pembangunan dan Parameter Keberhasilan
Peluang untuk mengubah paradigma ini masih tetap terbuka, melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri dengan turut serta melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merancang strategi yang lebih agresif untuk menjembatani kesenjangan ini. Pemerintah perlu mendorong kebijakan “Domestic Content Requirement” yang bersifat strategis dan terukur.
Daripada sekedar memberikan insentif bagi industri di dalam FTZ, pemerintah dapat membuat aturan yang memberikan kemudahan tambahan bagi perusahaan di FTZ yang mampu menyerap sejumlah persentase bahan baku atau komponen dari wilayah non-FTZ di dalam Provinsi Kepri. Kebijakan ini akan memaksa terciptanya linkage dan integrasi antara industri inti di FTZ dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten/kota sekitarnya, sehingga akan menciptakan integrasi ekonomi wilayah.
Pembangunan infrastruktur konektivitas harus menjadi prioritas mutlak yang perlu dikerjakan segera oleh pemerintah. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa panjang jalan nasional yang layak di Provinsi Kepri memang bertambah, tetapi fokusnya juga harus diperluas ke infrastruktur maritim.
Keberadaan pelabuhan yang memadai dan menambah frekuensi serta rute transportasi pelayaran laut maupun penyeberangan yang menghubungkan pelabuhan hub di FTZ dengan pulau-pulau penghasil komoditas. Dengan biaya logistik yang turun dan kemudahan aksesibilitas maka daya saing produk dari daerah non-FTZ akan meningkat dan memberikan dampak pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Menciptakan pemerataan dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar FTZ. Infrastruktur logistik yang dibangun tidak akan berarti maksimal jika tidak diiringi dengan penciptaan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh. Upaya ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan kawasan klaster industri berbasis komoditas unggulan setiap pulau yang dapat menjadi mitra strategis bagi industri di FTZ, sehingga akan membentuk jejaring ekonomi kepulauan yang saling menguatkan.
Kemudian perlu komitmen anggaran yang strategis dan terarah dari pemerintah daerah yang fokus alokasinya pada program peningkatan kapasitas UMKM, pengembangan pusat-pusat logistik di daerah penyangga, serta beasiswa pendidikan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan industri di FTZ. Langkah ini merupakan bentuk dari redistribusi manfaat dan investasi jangka panjang untuk menyambungkan arah pembangunan antarkawasan FTZ dan non-FTZ yang selama ini terasa kurang menyentuh dalam konsep keterpaduan pengembangan kewilayahannya.
Keberhasilan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk dan ekspor yang dihasilkan oleh ketiga pulau tersebut. Namun, parameter lainnya juga harus ditetapkan untuk mengukur seberapa besar multiplier effect yang tercipta bagi kabupaten/kota lain? Berapa persen komponen lokal yang berhasil diserap oleh industri di FTZ? Seberapa banyak lapangan kerja di daerah non-FTZ yang tercipta akibat aktivitas FTZ? dan Bagaimana dampak terhadap pemerataan pembangunan wilayah?
FTZ Batam, Bintan, dan Karimun tidak boleh menjadi lumbung insentif yang hanya dinikmati segelintir pelaku usaha di dalam temboknya. Ia harus menjadi “jantung” yang memompa darah segar ke seluruh tubuh Provinsi Kepri. Perlu adanya perubahan mindset dari sekedar “mengelola kawasan” menjadi “mengintegrasikan wilayah” untuk membangun jembatan yang kokoh menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan. Tanpa upaya yang disengaja, sistematis, dan didukung oleh regulasi yang inklusif, FTZ hanya akan menjadi “menara gading” yang megah dan mewah, namun sunyi dari makna pemerataan bagi saudara-saudaranya di seberang pulau.
Biografi Singkat Penulis
Encik Ryan Pradana Fekri, ST.,M.PWK. aktif sebagai Praktisi di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga merupakan Pengajar di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung serta merupakan anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.