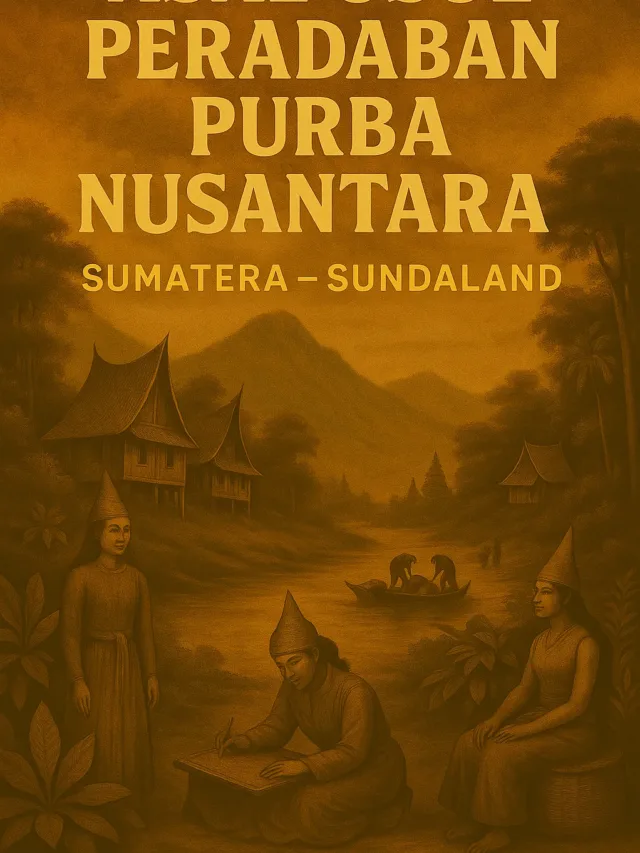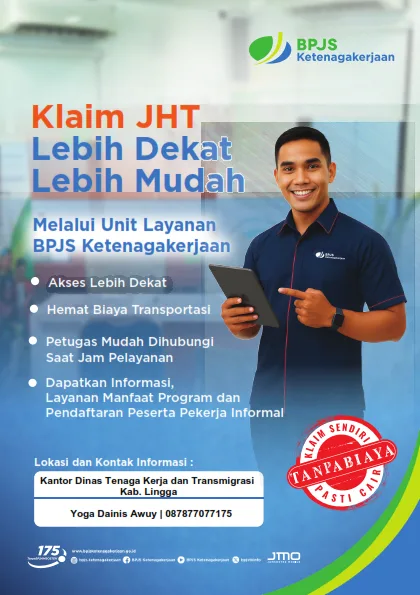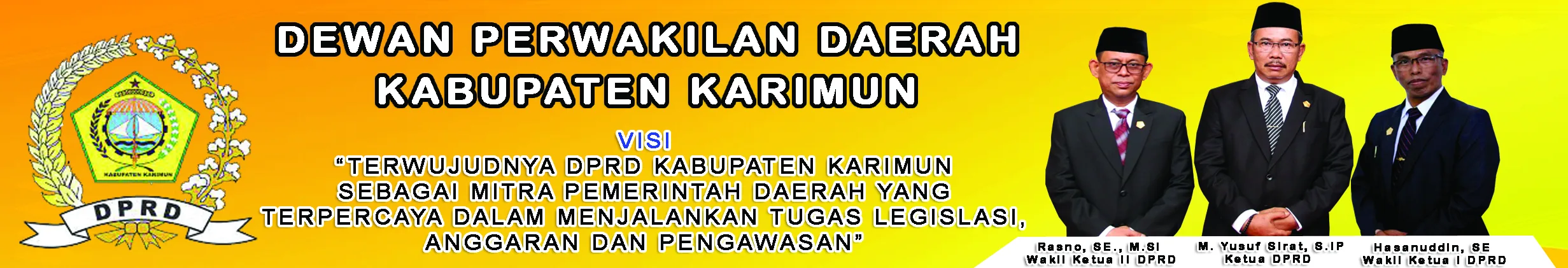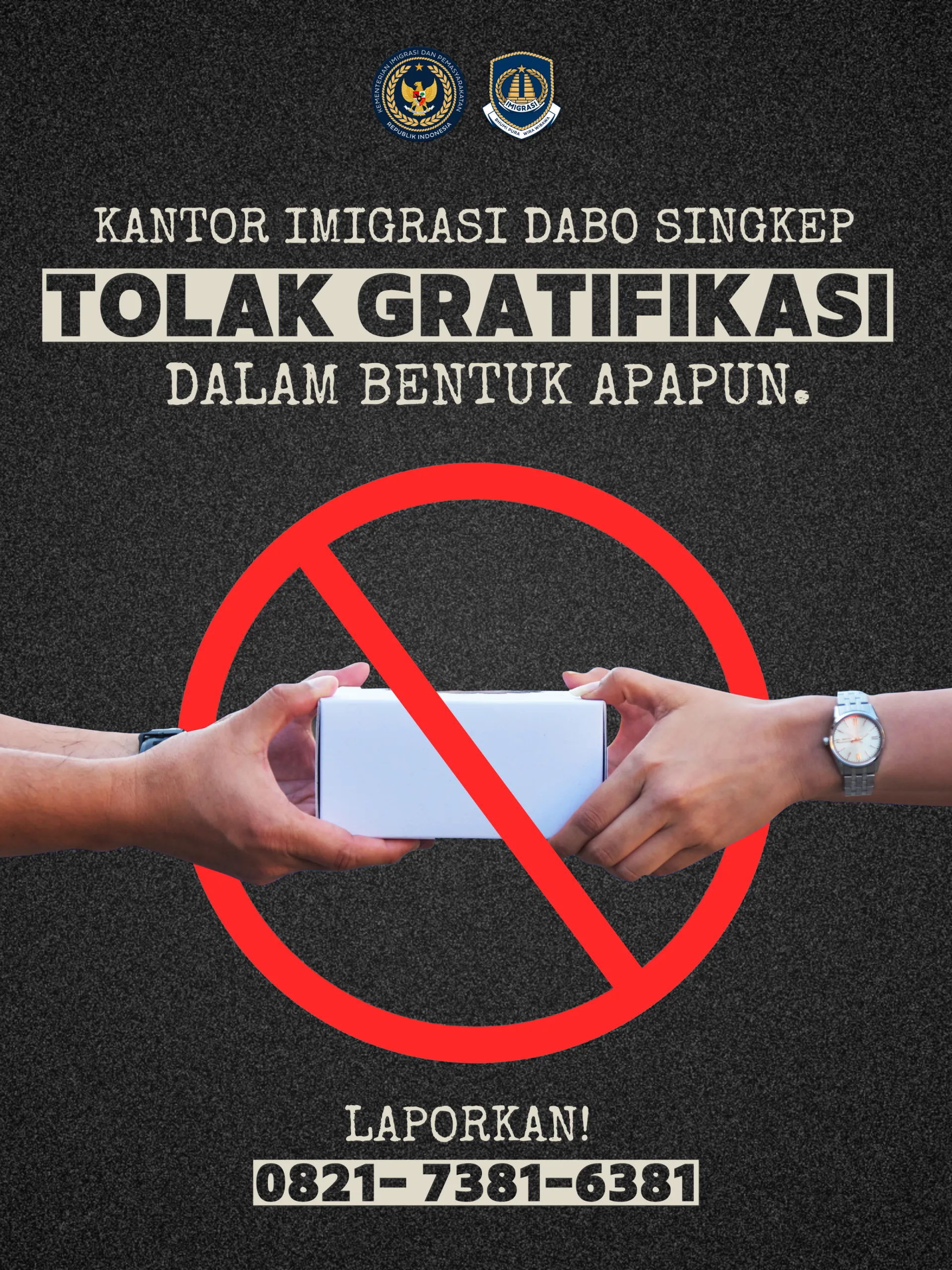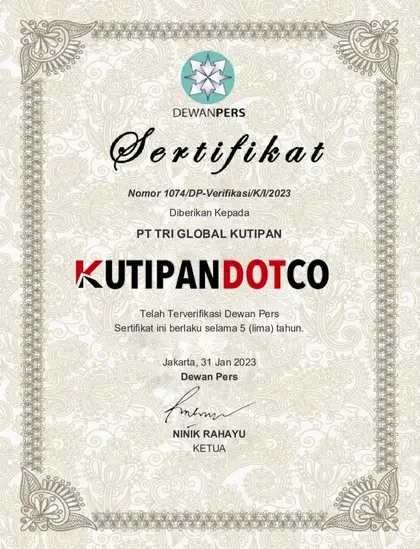KUTIPAN – Kalau mendengar kata “gamelan”, kebanyakan orang langsung membayangkan wayang kulit, Jogja, atau Surakarta, dua wilayah yang dianggap sebagai “rumah resmi” bagi alat musik berbilah logam itu. Tapi tunggu dulu, ternyata di ujung barat Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau, ada juga yang namanya Tari Gamelan, dan uniknya, bukan hasil impor budaya dari Jawa.
Tarian ini justru lahir dari tanah Melayu klasik pada abad ke-17, di tengah kemegahan istana Kesultanan Riau-Lingga. Dari gerakannya yang lembut, musik pengiring yang khas, sampai kostum penarinya yang berbalut selendang, kipas, dan suntiang di kepala, semuanya menyimpan kisah panjang tentang pertemuan budaya yang indah dan damai.
Ironisnya, di tanah asalnya sendiri, tarian ini justru kalah populer dibanding di Malaysia, terutama di Terengganu, di mana gamelan Lingga sering dimainkan dalam acara adat dan pernikahan. Sebuah ironi sekaligus pengingat, bahwa kadang sesuatu yang berharga justru lebih dihargai oleh orang lain.
Nama “Tarian Gamelan” muncul karena iringan musiknya memang memakai seperangkat gamelan, dengan total 77 instrumen pada masa kejayaan istana, meski kini hanya tersisa 33 jenis saja.
Beberapa nama alat gamelan bahkan terdengar puitis sekaligus jenaka, ada gamelan kunang-kunang mabuk, gamelan ketam renjung, hingga gamelan lantai lima. Setiap nama itu menggambarkan gerakan tarinya, hal yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara bunyi dan tubuh dalam kebudayaan Melayu klasik.
Awalnya, tarian ini hanya boleh ditampilkan di dalam istana. Namun seiring waktu, pintu istana dibuka dan masyarakat mulai bisa menyaksikan keanggunan Tari Gamelan secara luas.
Menurut catatan sejarah, pertunjukan pertama untuk publik terjadi pada tahun 1811, tepatnya di pernikahan Tengku Hussain, putra Sultan Abdul Rahman dari Lingga, dengan Wan Esah, adik Bendahara Ali dari Pahang. Dari situ, gema musik gamelan Melayu ini menyeberang ke Terengganu, dan kemudian berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.
Menariknya, walau memakai gamelan khas Jawa, gerak-gerak tarinya tetap menonjolkan identitas Melayu, lembut, gemulai, namun tetap tegas. Di sinilah letak keindahannya, dua budaya besar bersatu tanpa saling menelan satu sama lain.
Makna filosofisnya sederhana namun dalam, perpaduan budaya bukan ancaman, melainkan wujud harmoni. Seperti bunyi gamelan yang berpadu dengan gerak tubuh Melayu, keberagaman justru membuat seni semakin kaya.