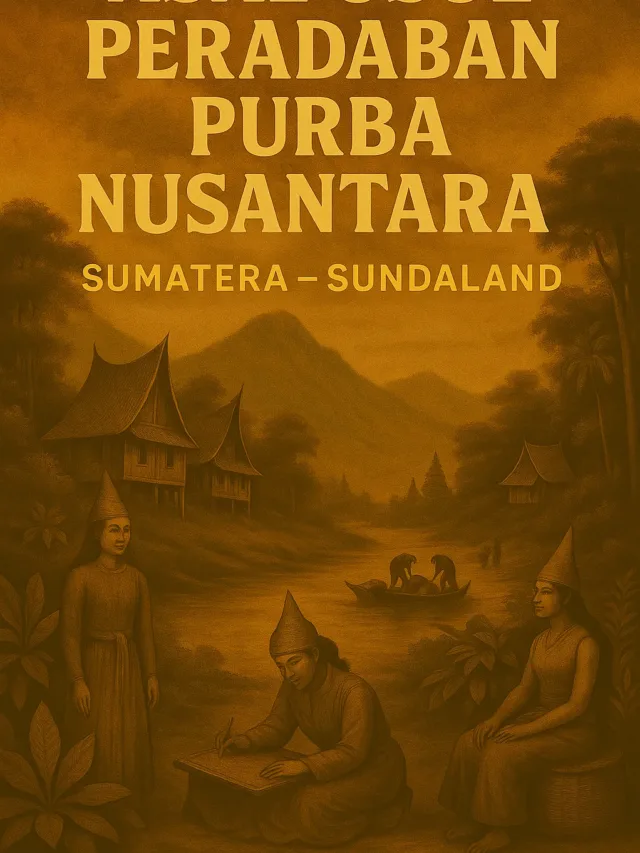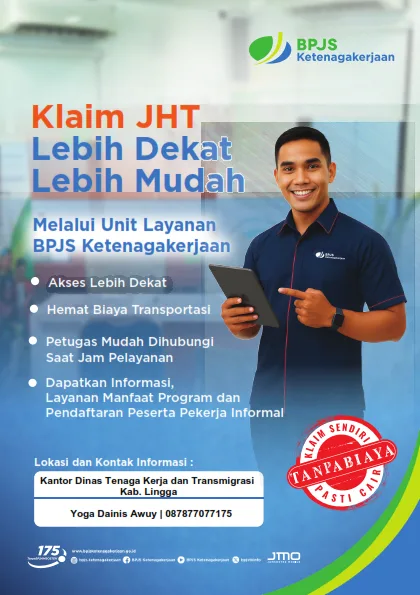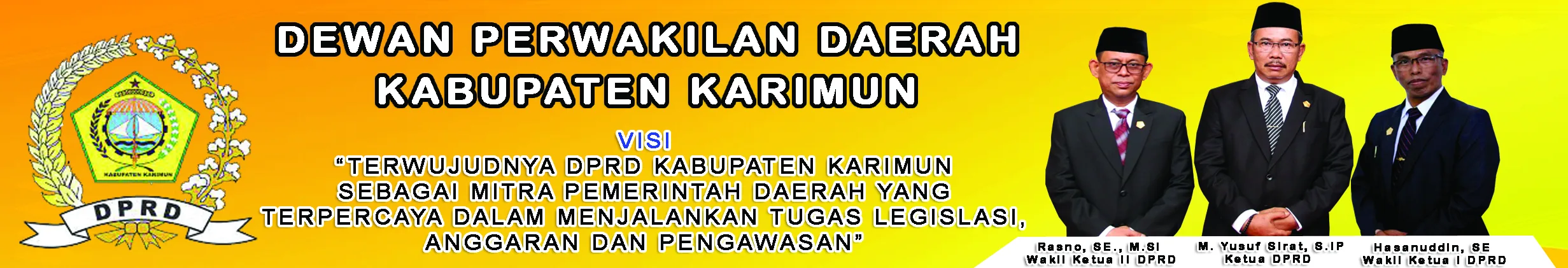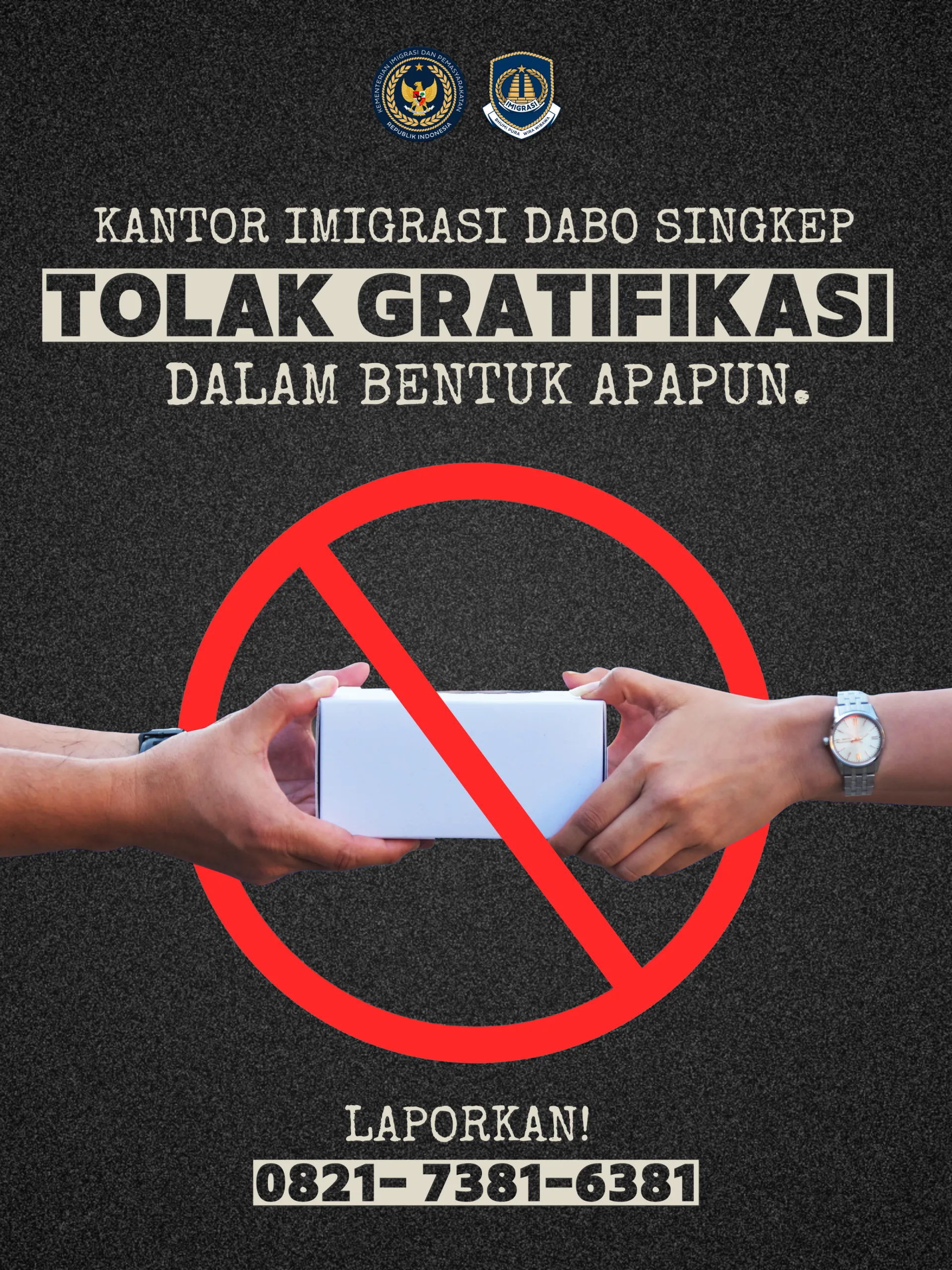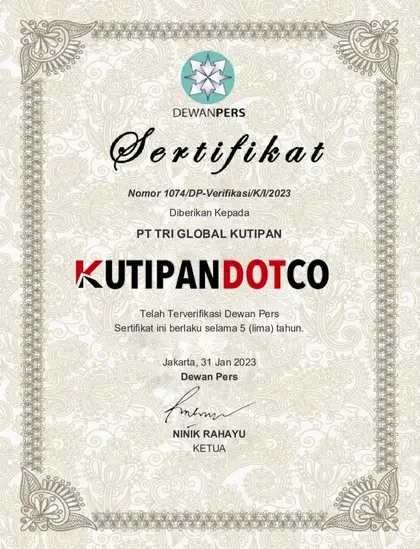Oleh: Encik Ryan Pradana Fekri, ST.,M.PWK.
(Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota, Pengajar di Institut Teknologi Nasional Bandung, Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia)
Pada 20 November 2003, Kabupaten Lingga resmi terbentuk sebagai daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau. Dua puluh dua tahun berselang, setiap peringatan hari jadinya selalu dirayakan dengan penuh semangat, dihiasi berbagai macam seremoni, baliho ucapan selamat, dan laporan keberhasilan pembangunan. Namun, peringatan hari jadi semestinya bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga momentum untuk meninjau kembali arah pembangunan: sudahkah pembangunan daerah yang telah berjalan selama dua dekade ini benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat Lingga dan menghadirkan kesejahteraan?
Kemajuan yang Terlihat, Ketimpangan yang Masih Nyata
Secara demografis, Lingga merupakan kabupaten kepulauan dengan populasi sekitar 102,95 ribu jiwa (BPS Kabupaten Lingga, 2025). Letaknya yang tersebar di gugusan kepulauan membuat persoalan pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri. Konektivitas antarpulau, distribusi layanan dasar, serta disparitas ekonomi menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah proyek infrastruktur. Ujian utama pembangunan Kabupaten Lingga adalah bagaimana menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah kondisi geografis yang terfragmentasi.
Dari sisi sosial-ekonomi, ada tanda-tanda kemajuan, namun juga sinyal peringatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lingga turun dari 14,05 persen pada 2022 menjadi 9,99 persen pada tahun 2025. Sebuah capaian yang menggembirakan karena menunjukkan perbaikan kesejahteraan. Meski demikian, jika dikonversi ke jumlah penduduk, berarti masih ada sekitar 9.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan sendiri meningkat dari Rp507.223 per kapita per bulan pada 2022 menjadi Rp562.906 per kapita per bulan pada 2025 (BPS Kabupaten Lingga, 2025), menandakan bahwa kebutuhan hidup layak juga semakin mahal. Artinya, kemiskinan di Lingga bukan semata soal rendahnya pendapatan, tetapi juga soal daya beli dan struktur ekonomi lokal yang belum kuat menopang kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang Berjalan, Nilai Tambah yang Tertinggal
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memang gencar membangun berbagai infrastruktur fisik. Capaian pembangunan infrastruktur meningkat dari 36,65 persen pada 2020 menjadi 54,86 persen pada 2023. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik baru bermunculan di berbagai wilayah. Namun pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: untuk siapa semua pembangunan ini dilakukan? Apakah pembangunan jalan dan pelabuhan benar-benar membuka akses dan peluang usaha bagi masyarakat serta menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, atau justru mempercepat arus keluar hasil sumber daya alam ke luar daerah tanpa nilai tambah bagi masyarakat?
Bukan berarti pembangunan infrastruktur tidak penting. Bagi wilayah kepulauan seperti Lingga, konektivitas fisik memegang peranan vital dalam menghubungkan antarwilayah. Tetapi pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Pembangunan jalan dan pelabuhan akan bermakna jika membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat, mendorong tumbuhnya usaha kecil, memperkecil ketimpangan antarpulau, serta mendukung kegiatan produktif berbasis potensi lokal seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Tanpa strategi ekonomi yang menumbuhkan nilai tambah di tingkat lokal, pembangunan infrastruktur hanya menjadi simbol, bukan alat untuk mencapai kesejahteraan yang merata.
Kabupaten Lingga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari hasil laut, perkebunan, pertanian, hingga potensi wisata bahari. Namun, sebagian besar hasil-hasil sumber daya alam tersebut masih dijual dalam bentuk mentah. Ironisnya, nilai tambah justru dinikmati pihak luar yang memiliki fasilitas pengolahan dan akses pasar lebih besar. Ketiadaan industri pengolahan di daerah membuat nelayan dan petani Lingga tetap berada pada rantai paling bawah dalam sistem ekonomi, padahal mereka yang paling dekat dengan sumber daya itu. Inilah potret pembangunan yang terasa berjalan, tetapi belum benar-benar mengubah kesejahteraan masyarakat.
Kesenjangan Pembangunan dan Lemahnya Kemandirian Daerah
Kesenjangan antarwilayah juga masih menjadi persoalan serius yang perlu terus dibenahi oleh pemerintah daerah. Kawasan yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta daerah yang lebih mudah diakses mengalami percepatan pembangunan, sementara pulau-pulau kecil dan desa-desa pesisir masih tertinggal. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas dan belum merata. Di sejumlah pulau seperti Posek, Benan, Berhala, dan Pekajang, masyarakat masih harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan kapal untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar atau mengakses sekolah menengah.
Menurut kajian Bappeda Provinsi Kepulauan Riau (2023), sebagian besar angkatan kerja di Lingga masih berpendidikan dasar, bahkan banyak yang tidak menamatkan sekolah menengah. Hal ini juga dibuktikan oleh data BPS Kabupaten Lingga (2025) yang menunjukkan bahwa sekitar 42,5 persen angkatan kerja di Kabupaten Lingga berpendidikan sekolah dasar. Akibatnya, sebagian besar masyarakat hanya mampu bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan mendasar bagi pembangunan daerah.
Persoalan lain adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lingga masih relatif kecil, sehingga ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan inovatif menjadi terbatas. Indikator kemandirian fiskal Kabupaten Lingga bahkan masih berada pada kategori “belum mandiri” (Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau, Triwulan II, 2025).
Dari total pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai Rp1 triliun, sekitar 89 persennya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi, sementara kontribusi PAD hanya sekitar Rp112 miliar atau kurang dari 11 persen. Angka ini menggambarkan betapa rapuhnya fondasi fiskal Lingga ketika sumber keuangan utama masih bergantung pada kebijakan anggaran pusat.
Mengubah Paradigma Pembangunan Daerah
Usia dua dekade Kabupaten Lingga seharusnya menjadi momentum untuk menilai kembali arah pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma pembangunan dari sekadar “berapa banyak yang dibangun” menjadi “seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat”. Ukuran keberhasilan tidak hanya dihitung dari panjang jalan atau jumlah proyek, tetapi juga dari peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan pemerataan wilayah, serta bertambahnya peluang kerja yang layak bagi generasi muda. Pembangunan harus berorientasi pada outcome dan impact, bukan sekadar output.
Anggaran daerah sebaiknya lebih banyak dialokasikan untuk belanja produktif dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya untuk belanja rutin birokrasi. Evaluasi kebijakan pun perlu berbasis data dan indikator yang dapat diukur secara jelas. Program perikanan misalnya, perlu diukur bukan hanya dari jumlah bantuan kapal atau alat tangkap, tetapi dari peningkatan pendapatan nelayan dan pertumbuhan usaha dalam pengelolaan hasil laut. Demikian pula program pariwisata, keberhasilannya harus diukur dari manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal, bukan sekadar jumlah kunjungan wisatawan.
Di sisi lain, pembangunan Lingga tak bisa dilepaskan dari identitas budayanya sebagai “Bunda Tanah Melayu” yang memiliki warisan sejarah panjang. Warisan budaya ini semestinya tidak dipinggirkan dalam narasi pembangunan modern, melainkan dijadikan fondasi moral dan sosial. Pembangunan yang berakar pada kearifan lokal akan lebih tahan terhadap guncangan sosial dan lebih diterima masyarakat, karena tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dalam keseharian.
Peringatan 22 tahun Kabupaten Lingga hendaknya menjadi titik balik untuk memaknai kembali arah pembangunan. Pembangunan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan menyejahterakan masyarakat. Lingga memiliki potensi besar dengan alam yang indah, budaya yang kuat, dan posisi strategis di jalur maritim Indonesia. Namun semua potensi itu hanya akan menjadi catatan di atas kertas jika tidak diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dua dekade adalah waktu yang cukup panjang untuk belajar dan berbenah. Kini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi seberapa banyak Lingga telah membangun, tetapi seberapa banyak pembangunan itu telah mengubah kehidupan masyarakatnya. Jika refleksi ini benar-benar dijadikan momentum untuk memperbaiki arah kebijakan, maka perayaan hari jadi ke-22 tidak akan sekadar menjadi pesta seremonial, tetapi menjadi tanda dimulainya babak baru pembangunan Lingga yang inklusif, adil, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakatnya.
Biografi Singkat Penulis Encik Ryan Pradana Fekri, ST.,M.PWK. aktif sebagai Praktisi di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga merupakan Pengajar di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung serta merupakan anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.